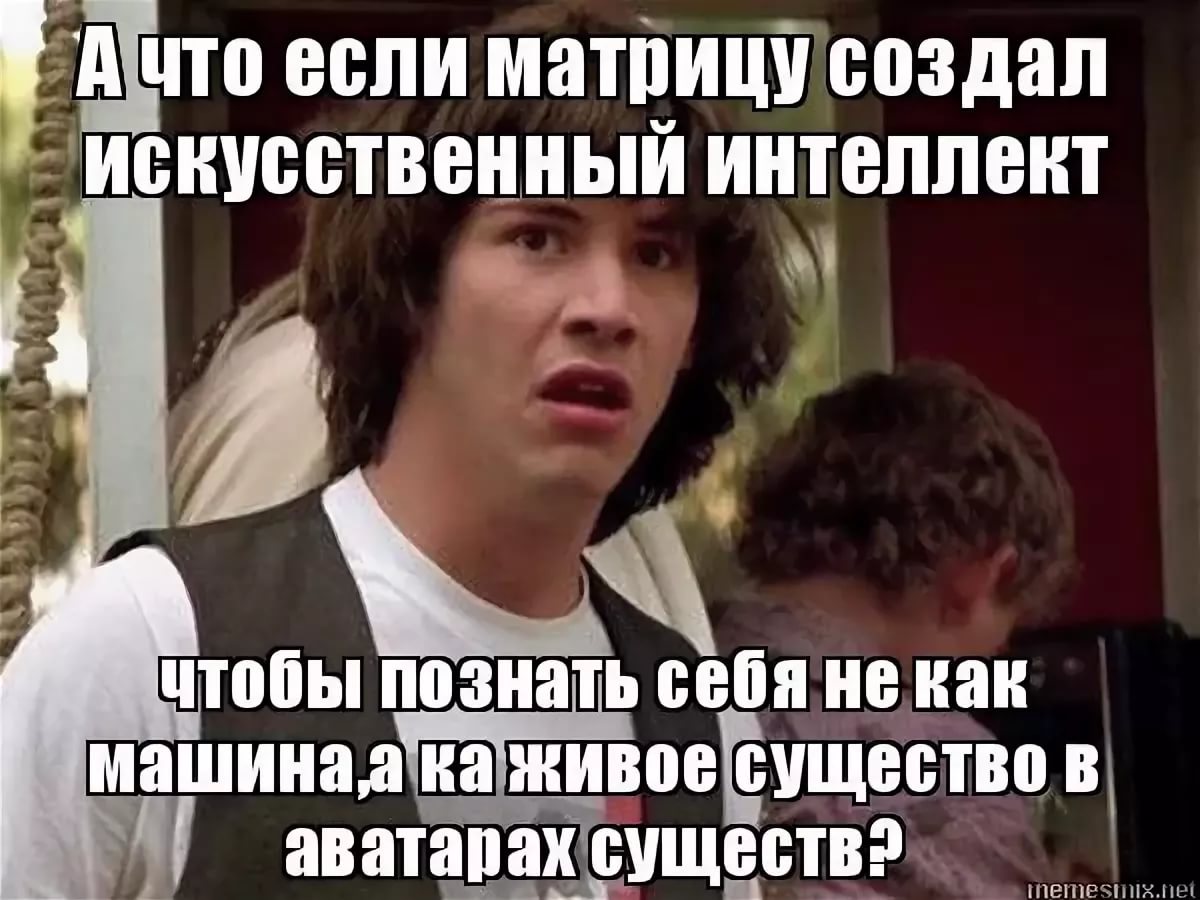Jika bagi sebagian orang masa depan dengan AI tampak seperti distopia yang suram atau perjuangan untuk bertahan hidup, mungkin mereka harus memilah ide-ide mereka tentang sifat kekuasaan dan penyerahan diri.
Demikian kata Stephen Cave, seorang peneliti senior di Leverhulm Centre for Study of Future Intelligence di University of Cambridge. Dalam esainya, ia menyarankan untuk mengeksplorasi sejarah superioritas intelektual - dan meninggalkan konsep yang salah ini.
Dunia progresif paruh kedua abad ke-20 didominasi oleh daya tarik dengan konsep kecerdasan buatan.
Mereka memikirkan kemampuan mental, mendiskusikannya, dan mengembangkan pendekatan baru untuk mengukurnya. Puluhan ribu remaja dan pencari kerja di negara-negara Eropa terkemuka telah lulus (dan sedang) mengikuti tes IQ.
Meski begitu, gagasan bahwa kecerdasan dapat diukur sebagai tekanan darah atau ukuran kaki bukanlah hal baru. Tetapi yang lebih tua adalah gagasan kami bahwa tingkat kecerdasan dapat menentukan posisi seseorang dalam kehidupan.
Pemahaman ini mengalir melalui seluruh sejarah pemikiran Barat, dari filsafat Plato ke keyakinan politisi modern.
Kecerdasan adalah Politik
Sepanjang sejarah, dunia Barat telah menentukan dalam hal kecerdasan apa yang dapat dilakukan seseorang untuk masyarakat. Sebagai contoh, kami secara tradisional (untuk mayoritas populasi) menghubungkan kemampuan mental tingkat tinggi dengan dokter, insinyur, dan
pejabat tinggi negara .
Kami percaya bahwa tingkat kecerdasan memberi kami hak untuk mengendalikan nasib orang lain: kami menjajah, memperbudak, merampas alat kelamin kami dan menghancurkan mereka yang kami anggap kurang cerdas dan berkembang.
Sikap kami terhadap kecerdasan mulai berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Dalam beberapa dekade terakhir, kami telah melihat kemajuan yang signifikan di bidang ini dan tampaknya berada di ambang terobosan ilmiah yang luar biasa. Menilai dengan jumlah memeplex dan lelucon tentang topik kecerdasan buatan, kami secara bersamaan senang dengan apa yang terjadi dan pada saat yang sama sangat ketakutan. Dan untuk memahami apa yang membuat kami sangat takut dan mengapa kami begitu acuh terhadap topik kemampuan mental, perlu untuk mempertimbangkannya dari sudut pandang historis dan politik dan untuk melacak bagaimana pemikiran filosofis mengubah kecerdasan menjadi alat untuk membenarkan penaklukan tanpa akhir.

Utas historis stereotip
Plato menjadikan pikiran suatu keharusan bagi yang kuatYang pertama tentang berpikir mulai memperdebatkan Plato. Dalam tulisannya, ia menganggap nilai khusus untuk proses refleksi, dengan alasan bahwa hidup yang tidak berarti tidak bernilai sepeser pun. Patut diingat bahwa Plato hidup di dunia di mana mitos dan kesadaran mistik merupakan lingkungan alami bagi pikiran manusia. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa seseorang dapat mengetahui dunia melalui pemikiran adalah sangat berani dan menarik pada saat itu.
Dalam mengumumkan dalam karyanya “Negara” yang hanya seorang filsuf yang dapat memerintah negara, karena hanya dia yang dapat mencapai pemahaman yang benar tentang berbagai hal, Plato melahirkan gagasan meritokrasi intelektual - gagasan bahwa hanya yang paling pintar yang dapat mengendalikan orang lain.
Gagasan saat itu revolusioner: ya, Athena sudah bereksperimen dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Tetapi persyaratan untuk para penguasa sangat samar: itu sudah cukup untuk menjadi warga negara laki-laki - tidak ada pertanyaan tentang tingkat kemampuan mental. Dan di daerah lain, kursi pemerintah dibagikan baik dengan keanggotaan dalam elit (aristokrasi), atau dengan pengangkatan oleh pemeliharaan ilahi (teokrasi), atau hanya dengan tingkat kekuatan (tirani).
 Lukisan "The School of Athens", tempat Leonardo dan Bramante digambarkan bersama dengan Pythagoras dan Aristoteles.
Lukisan "The School of Athens", tempat Leonardo dan Bramante digambarkan bersama dengan Pythagoras dan Aristoteles.Aristoteles datang dengan kekuatan manusia
Gagasan inovatif Plato berhasil mendarat di tanah subur para pemikir besar zaman itu, dan muridnya, Aristoteles, tidak terkecuali. Dia berbeda dari guru dalam pandangan dunia yang lebih praktis dan sistematis, jadi dia menggunakan "elemen rasional jiwa" untuk menciptakan konsep hierarki sosial alami. Dalam Politiknya, ia menyatakan:
"Bagaimanapun, dominasi dan penyerahan tidak hanya diperlukan, tetapi juga bermanfaat, dan sejak lahir, beberapa makhluk berbeda [dalam arti bahwa beberapa dari mereka seolah-olah ditakdirkan] untuk tunduk, yang lain untuk dominasi."
Berdasarkan hal ini, pria berpendidikan secara alami mendominasi wanita, pria pekerja fisik dan budak. Di bawah ini dalam hierarki adalah hanya hewan yang begitu tanpa alasan bahwa mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mengendalikan mereka.
Kami bahkan tidak memperhatikan bagaimana kami beralih dari gagasan Platonis tentang keutamaan elemen rasional ke konsep Aristotelian, yang mengandaikan kekuatan yang sepenuhnya alami dari manusia yang berpikir.Kereta ketidakadilan intelektual ini masih menggunakan bahan bakar, yang dipicu oleh dua pria berjanggut 2000 tahun lalu. Filsuf Australia modern Val Plumwood mengklaim bahwa dua raksasa filsafat Yunani, dipersenjatai dengan serangkaian dualisme yang meragukan, masih berhasil memengaruhi ide-ide kita tentang pikiran.
Karena kita memandang hubungan dominasi oleh hak yang paling cerdas sebagai sesuatu yang sepenuhnya alami, kita harus berterima kasih kepada Aristoteles.

Descartes meletakkan dasar moral untuk kehancuran planet ini
Filsafat Barat mencapai puncaknya dengan karya-karya dualis besar Rene Descartes.
Jika Aristoteles mengenali binatang setidaknya beberapa hak untuk minimal dan primitif, tetapi masih aktivitas mental, maka Descartes menyangkal hak ini sepenuhnya. Kesadaran, menurutnya, adalah keunggulan eksklusif manusia.
Filsafat Descartes merefleksikan milenium ideologi Kristen: ia memberi kepemilikan jiwa pada pikiran, percikan ilahi, yang hanya diwariskan kepada mereka yang beruntung yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Kant membenarkan kebijakan kolonial
Gagasan bahwa pikiran mendefinisikan seseorang telah melewati Pencerahan. Immanuel Kant - mungkin filsuf moralitas paling berpengaruh dari zaman kuno - percaya bahwa kehendak moral hanya khas bagi makhluk berpikir: "orang" dan "hal-hal dalam diri mereka". Makhluk non-berpikir, dalam pendapatnya, memiliki "hanya nilai relatif sebagai sarana dan karena itu disebut benda." Dengan mereka, Anda dapat melakukan apa yang kami inginkan.
Menurut Kant, makhluk rasional memiliki martabat, dan makhluk yang tidak masuk akal dan tidak berpikir tidak mampu melakukannya.Kesimpulan seperti itu kemudian menjadi landasan kebijakan kolonial.
Logikanya adalah ini: bukan orang kulit putih yang kurang cerdas; mereka tidak dapat secara mandiri mengendalikan diri dan wilayah mereka. Dan ini bukan hanya langkah yang dibenarkan, tetapi juga kewajiban moral setiap orang kulit putih - untuk memasuki negara mereka dan menghancurkan budaya mereka.
Konstruksi logis yang sama bekerja dengan sempurna untuk wanita yang dianggap terlalu sembrono dan rapuh untuk berbagi hak istimewa orang yang rasional.
Francis Galton adalah bapak psikometri, pseudosain dalam pengukuran pikiran, dan sepupu Charles Darwin. Terinspirasi pada zamannya oleh Origin of Species, Galton menciptakan konsep bahwa kemampuan mental diwariskan dan dapat ditingkatkan dengan seleksi.
Galton tidak terbatas pada perhitungan teoritis: dalam dekade-dekade berikutnya, lebih dari 20.000 wanita di California saja disterilkan setelah menerima hasil yang buruk dari tes Galton.

Jadi mengapa kita takut dengan robot pintar?
Mari kita kembali ke pertanyaan yang diajukan di awal artikel: mengapa kemungkinan munculnya kecerdasan buatan membuat kita takut? Apakah karena kita terbiasa dengan fakta bahwa yang pandai selalu mendominasi, dan kita jelas tidak ingin berada di sisi lain dari barikade?
Penulis dan sutradara telah lama berspekulasi tentang tema pemberontakan mesin.
Jika wajar bagi kita untuk berpikir bahwa kulit paling pintar dihilangkan dan bahwa satu negara yang lebih maju dapat menjajah yang lain, maka kita secara alami takut akan potensi perbudakan oleh mesin ultra-pintar. Kecerdasan buatan merupakan ancaman eksistensial bagi kita.
Bagi kami, ini untuk pria kulit putih Eropa. Miliaran orang lain telah melewati pengajuan selama berabad-abad, dan banyak yang terus memerangi agresor hingga hari ini, jadi bagi mereka ancaman perbudakan oleh kecerdasan buatan tetap menjadi cerita yang fantastis.
Laki-laki kulit putih Eropa sangat terbiasa berada di puncak dengan hak kepemilikan sehingga penampilan saingan yang mungkin ada dalam diri kita merespons dengan kengerian chthonic (irasional).
Saya tidak mengklaim bahwa kekhawatiran akan munculnya kecerdasan buatan yang kuat tidak berdasar. Ada ancaman nyata, tetapi tidak ada hubungannya dengan kolonisasi peradaban manusia dengan robot.
Daripada memikirkan apa yang harus kita lakukan dengan kecerdasan buatan, lebih baik memikirkan apa yang kita lakukan dengan diri kita sendiri.
Jika kecerdasan buatan dapat membahayakan kita, itu hampir pasti akan terjadi bukan karena keinginan AI untuk menaklukkan umat manusia, tetapi karena kebodohan kita sendiri, yang akan kehilangan kesalahan. Bukan kecerdasan buatan yang ditakuti, tetapi kebodohan alami.
Jika masyarakat diyakinkan bahwa orang yang paling bijak - bukan orang yang telah mendapatkan kekuasaan, tetapi orang yang berusaha menyelesaikan konflik - akankah kita lebih takut pada robot pintar daripada diri kita sendiri?